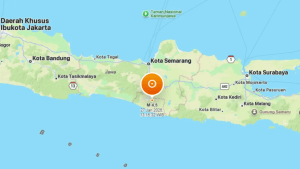Sore menjelang pelan di balik jendela, langit kota bergradasi jingga, dan bayang matahari memantul di lantai kamar yang dingin. Di kejauhan, suara azan berkumandang, samar-samar tenggelam di antara deru kendaraan dan hiruk pikuk dunia yang tak pernah benar-benar hening.
Di sudut kamar kecil di lantai satu sebuah asrama, aku duduk sendiri memandang senja, seolah menanti sesuatu yang tak juga datang. Tapi sejatinya, aku sedang mendengar bisikan suara yang hanya bisa dipahami oleh hati: suara kenangan yang mengaji dalam diam.
Sudah hampir dua tahun berlalu sejak aku meninggalkan pondok. Tapi hati ini tak pernah benar-benar pergi darinya.
Pondok tempat di mana waktu seolah bergerak lambat, namun hatiku tumbuh cepat. Tempat di mana subuh bukan hanya tentang bangun pagi, tapi tentang menyapa langit dengan tasbih dan menyiram jiwa dengan doa. Tempat di mana aku pertama kali mengenal makna sunyi yang menghidupkan, bukan yang menyakitkan.
Kini, hidupku bergerak cepat, sibuk, ramai, tapi… kosong. Tidak ada lagi suara teman sekamar yang membangunkan dengan suara lembut, “Qiyamul lail, yuk.” Tidak ada lagi lantunan ayat-ayat yang bersahut-sahutan dari kamar sebelah. Tidak ada lagi wajah Bu Nyai yang menatap tajam tapi penuh kasih saat aku lupa ayat lima pulu tiga surah Al-Ahzab.
Aku rindu makan dari nampan yang sama, rindu wudhu dengan air yang kadang nyaris beku, rindu duduk melingkar di atas tikar lusuh dengan kitab kuning di tangan membaca sambil mengantuk, tapi bahagia.
Dulu, aku mengira pondok hanyalah tempat tinggal sementara sebelum “dunia nyata” menjemput. Tapi nyatanya, justru di situlah aku menemukan dunia yang paling nyata dunia yang mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang tunduk, bukan hanya kepada guru, tapi kepada waktu, kepada sabar, kepada Allah.
Kini, setiap azan berkumandang, aku merasa ada sesuatu yang ditinggal di masa lalu. Setiap lembar mushaf kubuka, ada bayangan suara Bu Nyai membetulkan bacaanku dengan lembut. Setiap malam menjelang, aku mendongak ke langit mencari langit pondok yang dulu menjadi atap doaku.
Aku tahu aku tak bisa kembali menjadi santri yang seperti dulu. Tapi aku bisa tetap memelihara jiwa santri di tengah dunia yang gaduh ini.
Karena sejauh apapun aku melangkah, rindu itu selalu kembali mengaji di hatiku, menunduk di sujudku, dan menetes diam-diam bersama air mata yang turun di sepertiga malam.
Kanah Wulanah (CSSMoRA Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia)