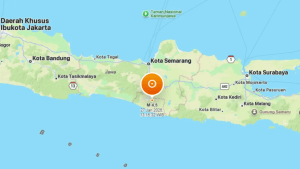"Mau dimasakin apa hari ini?" ucap Ibu yang sedang bersiap-siap untuk membeli bahan makanan di penjual sayur keliling.
Setiap pagi, ia akan bertanya soal makanan yang akan ia olah hari ini. Sebenarnya aku mulai kesal dengan pertanyaan yang berulang itu, aku selalu menggerutu diam-diam. Tidak bisakah dia langsung saja membeli bahan apa yang akan dimasak tanpa harus bertanya dulu? Hingga suatu hari, Ibu tidak bertanya lagi apa yang akan dia masak hari ini dan hari berikutnya. Meja makan tetap ramai beraneka macam makanan, tapi itu justru hal yang buruk. Tiap hari, sisa makanan menumpuk dan terbuang sia-sia. Aku enggan untuk makan karena lauk yang dihidangkan tidak sesuai dengan seleraku. Begitu pun ayahku, kulihat dia tidak makan selahap biasanya. Hanya Ibu yang tetap berantusias makan.
“Bu, aku mau makan sambal cumi dan udang crispy,” kataku sebelum Ibu pergi membeli bahan makanan. Dan akhirnya, setelah beberapa hari nafsu makanku menurun, sekarang mulai meningkat lagi. Tapi tak kulihat Ibu makan bersamaku. Aku pun memutuskan untuk mencari Ibu. Diam-diam kuamati dari balik pintu dapur, Ibu sedang makan di dapur dengan masakannya kemarin: sayur pare dan ikan lele. Aku menelan ludahku yang kelu dan kembali ke meja makan.
Aku masih memikirkan Ibu hingga aku beranjak ke tempat tidur. Oh, Ibu… apa yang ia lakukan?
CEKLEK! Suara pintu terbuka. Aku terkejut dan harus segera menutup mataku. Ibu, dia selalu datang ke kamarku sebelum ia tidur, berdiri sejenak di depan pintu yang tak sepenuhnya terbuka.
“Mau makan apa hari ini?” ucap Ibu kembali.
Pagi ini aku sarapan dengan nasi goreng dan telur ceplok setengah matang. Ibu juga membekaliku dengan nugget dan sayur kangkung. Dulu, ketika aku masih di bangku sekolah dasar, Ibu akan mengantarku sampai halte bus dan menjemputku di tempat yang sama. Tapi sekarang, aku mengatakan padanya kalau aku sudah berani pergi ke halte bus sendiri, jadi dia bisa mengerjakan urusan rumah yang lain. Namun, Ibu tetaplah Ibu. Walaupun dia tidak mengantarku sampai halte bus lagi, ia akan melihatku dari teras depan sampai punggungku tak nampak lagi. Tak sampai di situ, aku juga harus mengabarinya kalau aku sudah sampai di kelas dan ketika hendak kembali ke rumah. Jujur saja, aku mulai malas dengan Ibu yang terasa posesif dan menyebalkan. Aku merasa tidak bebas karena dia yang selalu menanyakan ini-itu, di mana dan kapan, setiap kali aku sedang menghabiskan waktu bersama teman-temanku, bahkan di hari libur.
Setelah beberapa tahun berlalu, kini aku pergi merantau, melanjutkan pendidikanku di perguruan tinggi. Tak ada lagi Ibu yang mengulang pertanyaan, “Mau makan apa hari ini?”
Tak ada lagi Ibu yang memastikan aku sudah tertidur setiap malam dan lain-lain. Kini, dunia
terasa sepi dan membosankan. Aku tak lagi bersemangat makan, berat badanku pun turun.
Ternyata, semua yang Ibu lakukan sudah menjadi kebiasaanku setiap harinya.
Aku mulai merasa kehilangan bagian dari diriku. Selama ini, Ibu menumpahkan cintanya di cangkir kecil yang kini menjadi teko besar. Terbayang, betapa sulitnya menjadi Ibu yang selama ini lelah mengurusi semuanya. Yang selalu menangis bahkan sejak pertama aku dilahirkan sampai seiring berjalannya waktu aku mulai melontarkan kata-kata kasar padanya. Yang selalu menyisihkan makanannya untukku karena aku menyukainya. Yang mengorbankan berbagai makanan yang ia suka demi makananku. Yang perhatiannya selalu aku cibir berulang kali. Pernah aku melihatnya menangis di atas sajadah ketika ia melakukan salat malam. Dia merapalkan banyak doa untukku dan keluarga. Dan di akhir, dia mengatakan “Ampuni hamba kecilmu ini ya Allah, yang masih belum bisa menjadi hamba serta istri dan ibu yang sempurna untuk anak dan suamiku. Lapangkan dan lindungi hati hamba dari kotornya perasaan hamba yang tak tentu agar hamba bisa menyelesaikan tugas hamba dengan baik.”
Di sela derita yang menjalar seperti akar dalam tanah lembab, semesta berbisik, "Kau tak boleh menyerah." Ibu hidup bukan untuk dirinya, tapi untuk dunianya. Bagi Ibu, hidup mencambuk namun juga menahan. Bukan rumah yang penuh pangkuan, melainkan lorong dingin dengan suara-suara yang tak bertuan.
Dunia—bukan Ibu—hanya semesta senyap yang kadang tersenyum, tapi lebih banyak mencaci.
Dian Elsaningtyas (CSSMoRA Universitas Wahid Hasyim 2023)