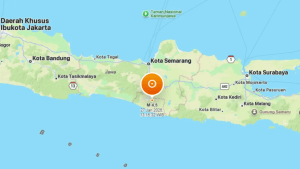Sebagai seseorang yang baru saja masuk ke dunia organisasi, awalnya saya berpikir bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang dan didengar. Saya membayangkan organisasi sebagai ruang belajar yang terbuka, di mana siapa pun terlepas dari latar belakangnya bisa menyuarakan pendapat dan mengambil peran. Tapi, seiring waktu saya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tak kasat mata namun sangat memengaruhi siapa yang mudah mendapat tempat dan siapa yang harus berjuang ekstra keras untuk diakui. Rasanya seperti ada “aturan tak tertulis” yang membuat sebagian orang lebih cepat dikenal dan dipercaya, sementara yang lain hanya jadi penggembira.
Dari pengamatan sederhana, saya mulai paham bahwa ini bukan soal siapa yang paling niat atau paling rajin. Kadang yang lebih cepat naik ke posisi penting justru mereka yang sudah punya “modal” sejak awal. Ada yang dekat dengan senior, ada yang gayanya komunikatif banget, atau bahkan hanya karena berasal dari latar belakang sekolah atau pesantren yang dianggap keren. Saya sempat merasa ini semua nggak adil, tapi kemudian saya ketemu dengan pemikiran sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu, yang bikin saya semakin sadar bahwa apa yang saya alami di organisasi ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah.
Menurut Bourdieu, setiap orang membawa habitus, yakni pola pikir, kebiasaan, dan cara bersikap yang terbentuk dari pengalaman hidupnya. Habitus ini kemudian berinteraksi dengan modal yang dimiliki seseorang: modal budaya seperti kemampuan bicara atau wawasannya, modal sosial seperti kenalan atau jaringan pertemanan, dan modal simbolik seperti status atau pengakuan dari orang lain. Semua itu akan beradu dalam sebuah arena, dan dalam konteks saya, arena itu adalah organisasi. Jadi, seseorang yang sudah terbiasa tampil, punya relasi luas, dan bisa menyesuaikan diri dengan budaya organisasi, jelas punya keunggulan sejak awal. Sebaliknya, orang-orang seperti saya yang masih kaku, minim koneksi, dan belum tahu “aturan main”-nya, kadang harus menunggu lebih lama untuk dianggap.
Yang bikin saya gelisah, pola-pola ini seringkali diterima begitu saja oleh para anggota organisasi, seolah itu sudah kodrat. Padahal, kalau dibiarkan, budaya semacam ini bisa menutup pintu bagi banyak orang yang sebenarnya punya potensi besar. Banyak teman saya yang akhirnya memilih diam, bahkan mundur, karena merasa organisasi tidak memberi mereka tempat. Ada semacam dinding tak terlihat yang memisahkan “yang punya akses” dan “yang biasa-biasa saja”.
Menurut saya, organisasi perlu berani membuka ruang baru yang lebih setara. Komunikasi harus dibangun bukan dari atas ke bawah, tapi dari semua arah. Senioritas seharusnya bukan jadi alasan untuk mendominasi, melainkan jadi sumber pengalaman yang membimbing. Mekanisme pemilihan pengurus juga harus transparan, supaya semua orang merasa prosesnya adil. Saya percaya, kalau organisasi mau benar-benar jadi ruang belajar, maka ia harus berani menata ulang budayanya, bukan cuma struktur formalnya, tapi juga cara pikir yang selama ini dianggap normal.
Bagi saya yang masih belajar, memahami dinamika ini memang nggak mudah. Tapi saya bersyukur bisa mulai melihat bahwa di balik struktur dan program kerja organisasi, ada dinamika kekuasaan yang dipengaruhi oleh hal-hal yang sering kali tidak kita sadari. Lewat kacamata Bourdieu, saya merasa lebih paham bahwa perubahan organisasi nggak cuma soal ganti pengurus atau bikin program kerja keren, tapi juga soal menciptakan budaya yang benar-benar membuka ruang bagi semua. Karena semua orang punya potensi, tapi tidak semua diberi kesempatan yang sama. Dan di sanalah seharusnya organisasi mengambil peran.
Konah Wulanah (CSSMoRA Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2023)