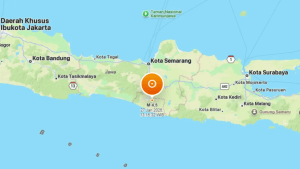Matahari selalu menepati janji, selalu menjanjikan cerah setelah badai. Matahari selalu menepati janji, akan ada terang setelah gelap. Matahari selalu menepati janji, selalu terbit bahkan di hari yang paling buruk seumur hidupmu.
7 tahun berlalu, berlalu dengan sesukanya. Tidak ada yang menarik dan hari ini adalah hari tepat setelah 7 tahun itu aku kehilangan matahariku. Siang ini, setelah sepulang sekolah aku berniat membeli mawar putih untuk dihadiahkan kepada ibuku.
“Hai Mam, lihatlah apa yang kubawa, mawar putih kesukaanmu. Tapi sebelum itu, aku akan bercerita. Hari ini Bu Jasmin meminta kita untuk melukis sesuatu yang kita suka. Dan tebak apa yang ku gambar, aku menggambar mawar putih ini Mam. Nah, lihatlah!“.
Kataku sambil memperlihatkan gambarku kepada beliau yang seolah-olah memperhatikannya. Sepi. Tak ada jawaban apapun. Aku menunduk, air mataku hampir luluh, tapi dengan sigapnya aku langsung mengusap air mata itu lalu tersenyum nanar.
“Hari ini seperti biasa, Papa sedang sibuk. Tapi tak mengapa, aku akan bilang kalau aku sudah mengujungimu. Baiklah aku akan pulang sebelum Papa tiba di rumah dan menemukan aku tak ada di sana. Jagalah dirimu disana Mam, dan sering-seringlah datang ke mimpiku. Aku teramat sangat merindukanmu.“
Aku meletakan mawar putih yang tadi kubeli diatas gundukan tanah itu, lalu pergi meninggalkannya.
Hari ini cuaca mendung, matahari enggan untuk menampakkan dirinya. Langit biru diselimuti awan keabu-abuan. Redup. Angin sepoi mengibaskan anak rambutku beberapa kali. Hari ini aku pulang dengan gundah kerinduan kepada ibuku.
Setibanya di rumah, aku mendapati terdapat sepasang high heels berwarna hitam berkilau yang cantik. Aku bisa membayangkan betapa anggunnya seorang wanita ketika memakainya. Seperti mama yang sangat menyukai high heels bahkan memiliki rak koleksi high heels tersendiri. Aku lanjut berjalan acuh, hanya melirik sekilas. Teman kantor Papa. Oke, aku kembali berjalan ke tangga menuju kamar.
“Sayang, kau kah itu? Dari mana kamu, kenapa baru sampai? Papa menunggumu sejak tadi. Ganti bajumu lalu kemarilah kita makan bersama. Oh iya, lihatlah siapa yang ayah ajak kemari. Ayo, jabat tangannya terlebih dahulu.”
Wanita itu melambaikan tangannya menyapaku. Ia tersenyum ramah memperlihatkan gigi rapinya. Bukan hanya itu, ia memiliki lesung pipi di sebelah kiri pipinya. Berbanding terbalik denganku yang memiliki lesung di pipi kananku. Rambut ikalnya dibiarkan tergerai, sangat cocok dengan penampilan feminimnya. Kemeja maroon dan rok hitam di atas lutut persis. Cantik sekali. Aku datang menghampirinya yang duduk di sofa ruang tengah.
“Hai, cantik. Nama kamu Adel, bukan? Wahh, ternyata kamu tidak seperti yang kubayangkan. Papamu bilang kau pendiam dan acuh terhadap sekitar. Tapi lihatlah! Kau ramah dan sangat cantik, sepertinya aku agak iri terhadap parasmu, ahaha. Tidak, sayang, aku bercanda. Namaku Clara.”
Katanya sambil menjulurkan tangannya. Aku membalas jabatan tangannya.
“Terima kasih.”
Hanya itu yang aku ucapkan. Papa mengusap puncak kepalaku lembut.
“Sayang, Bibi Clara akan lebih sering berkunjung untuk menemanimu. Ia akan segera menjadi ibumu.”
DUARRR! Suara petir menyambar senada dengan isi hatiku. Gumuruh di kepalaku tak bisa dideskripsikan.
“NGGAK! Adel nggak akan punya ibu lagi. Ibu Adel cuma Mama!”
“Sayang, tolong hargai keputusan Papa, ini juga demi kebaikanmu. Berilah peluang untuk Bibi Clara, Sayang.”
Papa memohon kepadaku.
“Apakah perkataan Adel kurang jelas? Sampai kapanpun Adel tidak akan punya Ibu lagi!”
Aku membalikkan badanku dan hendak pergi dari sana, tapi Papa menahan pergelangan tanganku.
“APA? Tolong jangan paksa Adel, Pa. Adel masih belum terbiasa dengan semua ini. Bahkan Papa hari ini tidak mengunjungi makam Mama. Adel minta maaf. Adel akan kembali ke kamar terlebih dahulu.”
Papa masih menahan pergelangan tanganku. Enggan melepasnya. Aku menatap sendu memohon. Air mataku sudah luluh sedari tadi. Bibi Clara mengusap pundak Papa, menenangkan. Akhirnya Papa melepaskan pergelangan tanganku. Aku beringsut ke lantai 2 menuju kamarku. Menutup pintu lalu menjatuhkan diri ke atas kasur. Membenamkan wajahku ke bantal dan terisak di sebaliknya. Hatiku sakit sekali.
Aku beralih mengambil foto kecilku bersama Papa dan Mama. Di sana aku mengenakan dress berwarna pink softy di gendongan Papa. Di sampingnya adalah Mama yang tersenyum bahagia.
7 tahun lalu, aku baru keluar dari kelas kanak-kanakku. Seperti kalian tau, anak seusia itu masih sering dijemput oleh orang tuanya. Papa bekerja seperti biasa, jadi Mama yang biasa menjemputku. Hari itu, ketika semua teman-temanku sudah dijemput oleh orang tua mereka, aku masih mencari keberadaan Mama. Tak lama setelah itu, Mama keluar dari mobil di seberang jalan. Melambaikan tangan kepadaku. Aku tersenyum senang melihat Mama, begitupun Mama yang sudah antusias untuk menghampiriku.
Lalu tiba-tiba BRAKKKK!!! Suara mobil menghantam. Mama terpental jauh dari jalan, bertubrukan dengan mobil itu. Di depan mataku. Aku menjerit memanggil Mama. Hendak berlari menghampirinya. Kemudian datanglah berbondong-bondong orang mengerumuni. Aku berlari membelah ramainya orang-orang. Memanggil-manggil Mama dan terisak.
“S-selamat ulang tahun, anak Mama…”
Kata Mama terbata-bata sambil berusaha keras meraih puncak kepalaku. Di tangan kirinya ada boneka kelinci yang merupakan hadiah ulang tahunku dari Mama. Dalam hitungan 3 detik, tangan Mama jatuh, lemas tak berdaya. Matanya menutup. Darah mengalir dari kepalanya. Ribut orang-orang tidak bisa mengalahkan ributnya kepalaku saat itu.
Tak lama kemudian, mobil ambulance tiba dan Mama dilarikan ke rumah sakit terdekat. Aku ikut mendampingi Mama. Para perawat berlari-lari menyambut Mama. Aku menggenggam tangan Mama. Tapi setelah itu, genggaman tanganku terlepas beriringan dengan masuknya Mama ke ruang bertuliskan ICU. Aku terisak lalu Papa datang. Aku berlari menghambur ke pelukannya. Papa memelukku erat. Menenangkanku yang semakin terisak. Namun nihil, Mama lebih memilih untuk mendekap pelukan Tuhan dibanding membalas pelukanku.
Tak sadar air mataku luluh kembali. Jatuh ke bingkai kaca foto tadi. Aku mengusapnya membersihkan. Sepertinya aku terlalu lelah memikirkan semua ini. Mataku terpejam dan aku jatuh tertidur.
Tok! Tok! Tok! Suara dari jendela kamarku membuatku terbangun. Aku beranjak dari tempat tidur dengan kepala yang berat. Melihat ke arah jendela. Langit sudah berubah ke semburat keoren-orenan. Ada burung kecil di depan jendela. Ketika aku hendak menghampirinya, burung itu terbang meninggalkan sehelai bulunya. Aku mengambil bulu itu dan melihatnya intens. Bulu yang cantik. Berwarna biru dengan gradasi kuning menyala. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka menampakkan Papa di sebaliknya.
“Sayang, ayo makan,” ajak Papa.
“Adel tidak lapar, Pa.”
“Kau belum makan sejak tadi, sayang.”
Aku mengalah mengikuti Papa ke lantai dasar. Bibi Clara sudah tidak ada, tapi ada berbagai menu tersaji di atas meja yang tak seperti biasanya. Dulu sewaktu Mama masih ada, meja makan tidak pernah sepi. Mama memasak segala macam menu yang rasanya mengalahkan masakan restoran bintang lima. Tapi setelah Mama pergi, meja makan berubah menjadi sepi. Setiap hari Papa memasak untukku sebelum berangkat ke kantor dan pulang membawakan makanan atau kadang juga memasak makan malam.
Papa memang sengaja mengurus rumah sendiri dan tidak melibatkan asisten rumah tangga, agar aku terus merasakan kehangatan rumah ini. Dulu ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Membersihkan rumah, memasak bersama, piknik di pelataran rumah, bahkan berkemah di sana. Semua itu seru sekali. Setelah Mama pergi, aku menjadi tidak berminat melakukan semua itu. Papa masih sering merayuku untuk melakukan semua aktivitas kami seperti dulu, tapi kenyataannya yang kulakukan hanyalah mengurung diri di kamar, membaca buku entah buku pelajaran atau novel, menggambar, melukis, menonton film, dan lainnya. Kami jarang berinteraksi secara intens karena kupikir tak ada hal menarik yang harus kita bicarakan.
Di sekolah, aku unggul di beberapa mata pelajaran dan aku masih menjadi juara bertahan di kelasku. Aku bahkan sering diutus untuk ikut perlombaan dan membawa pulang berbagai piala. Tapi biarlah. Aku bahkan tidak merasakan bangga pada diriku. Satu-satunya sesuatu yang kumau adalah membuat orangtuaku bangga, tapi sekarang aku tak tahu untuk siapa aku melakukan semua itu. Papa lebih sering menghabiskan waktunya di dunia pekerjaan, dan aku? Lagi-lagi sendiri. Aku tidak memiliki teman baik seperti sahabat karena aku enggan untuk berinteraksi. Aku terbiasa dengan kesendirianku, dan itu lebih baik.
Aku duduk berhadapan dengan Papa. Sunyi. Tidak ada suara kecuali dentuman sendok dan piring.
“Bagaimana sekolahmu hari ini, sayang?”
Papa membuka percakapan.
“Seperti biasa.”
Jawabku singkat tanpa melirik ke arahnya. Papa menghela napas pelan.
“Sayang, Papa minta maaf untuk hari ini. Satu hal yang perlu kau tahu, Papa melakukan semua ini untuk kebaikanmu. Papa tidak mau kau terus-terusan menyendiri dan mengurung diri di kamar. Bibi Clara adalah wanita yang baik. Papa sudah mempertimbangkan hal ini sebaik mungkin. Tolong buka hatimu untuk menerima dia ya, sayang.”
“Adel kenyang, Pa.”
Aku beranjak dari meja makan dan pergi melenggang meninggalkan makananku yang belum habis. Sebenarnya masakan Bibi Clara sangat lezat, tapi aku sedang malas untuk membahas ini lagi. Aku bahkan tidak masalah, jika harus hidup seperti ini sampai akhir hayatku. Bisa kulihat dari raut wajah Papa, dia sangat mengkhawatirkanku. Hari ini begitu kacau.
Pagi hari, sinar matahari mulai menyelinap masuk ke dalam kamarku lewat jendela, membuat ruang ini lebih terang. Aku masih tertidur sebelum suara kicau burung yang terus-terusan membuat suara ribut. Aku terbangun. Mengerjap-ngerjapkan mataku yang masih berat, kemudian memicingkan mata ke arah jendela dan mendapati seekor burung di sana. Aku tertarik untuk beranjak dari tempat tidur dan menghampiri burung itu. Aku mengambil tidak lebih dari segenggam cookies yang sudah aku tumbuk menjadi serpihan kecil-kecil. Aku membuka jendela lalu memberikan serpihan roti tadi kepada burung itu. Burung itu tampak mematuki roti yang kuberi, sepertinya ia suka. Aku hendak memegang burung itu, namun burung itu terbang dan meninggalkan sehelai bulunya. Aku tersenyum sambil memegang bulu itu.
Aku membersihkan diriku lalu membersihkan kamarku. Kemudian karena aku sudah mulai merasa lapar, aku turun ke lantai dasar. Terdengar ada dentingan sendok dan alat makan lainnya. Aku semakin mendekati meja makan, di sana aku melihat sesosok wanita dengan dress lengan pendek berwarna biru langit yang berenda putih, rambutnya terikat tinggi tampak sedang menyiapkan sesuatu di meja makan. Kemudian wanita itu membalikkan badannya, aku pura-pura tidak terkejut dan mencoba bersikap tenang. Bibi Clara. Ia selalu cantik dan menawan.
“Selamat pagi, cantik. Bagaimana tidurmu malam ini?” Tanyanya ramah dan dengan senyum manisnya tentu.
“Biasa saja,” jawabku ketus.
Aku melenggang ke meja makan dan lihatlah begitu banyak makanan yang sudah tersaji di sana. Ada ikan-ikanan, cumi saus hitam, sayur sup, ayam panggang, lalapan, dan bahkan ada buah-buahan dan juga jus. Sudah lama sekali sejak Mama tiada, aku tidak pernah melihat meja makan seramai ini. Jujur saja ketika melihat semua hidangan ini, nafsu makanku bertambah.
“Ayo makan, sayang,” ajak Bibi Clara.
“Jangan lupa cuci tanganmu terlebih dahulu ya.”
Deg! Aku teringat Mama. Ia selalu memarahiku karena aku selalu lupa untuk mencuci tanganku sebelum makan. Perasaan apa ini?
“Papa kamu sudah sarapan sedari tadi, dan sekarang ia sedang pergi bermain golf bersama teman-temannya.”
Bibi Clara berbicara seperti membaca pertanyaan di pikiranku yang sedari tadi mencari Papa. Aku diam saja tak menjawab. Melanjutkan sarapan pagiku.
“Bagaimana denganmu, sayang? Apa yang akan kau lakukan hari ini?”
“Berdiam diri di kamar,” jawabku.
Bibi Clara membereskan meja makan setelah aku dan dia selesai makan. Lalu aku naik menuju kamarku. Hari ini adalah hari libur. Aku tidak punya rencana apapun kecuali melakukan hal-hal yang menyenangkan di kamarku. Hari ini aku akan melukis burung itu. Aku sudah mempersiapkannya, mulai dari berbagai cat pewarna, kuas dari segala ukuran, kanvas, meja kanvas, palet, oil painting, cemilan, dan lainnya. Sebelumnya aku sudah membuat pola untuk burung di depan jendela.
Kemudian aku mulai menggradasikan warna biru dongker, lalu biru tua, kemudian biru muda dan warna putih untuk memblok sebagian besar kanvasku. Kemudian kutambahkan sedikit warna kuning pastel, oranye terang, dan putih untuk membuat pencahayaan. Lalu di paling dasar aku menggunakan warna coklat muda dan tua untuk tanahnya. Kemudian aku mulai memulaskan warna untuk burung itu dan pohon. Dalam waktu 2 jam lebih, aku sudah menyelesaikan lukisanku. Aku membiarkan lukisan itu kering terlebih dulu. Sementara itu, aku membereskan peralatan melukisku dan membersihkannya.
Di hari-hari selanjutnya, benar saja, Bibi Clara sering berkunjung ke rumah, entah murni berkunjung atau yang lain, tapi memang sejak Bibi Clara di sini, rumah jadi lebih terurus.
Hari ini aku pulang lebih awal karena para guru akan melaksanakan rapat. Aku sangat berantusias untuk kembali ke rumah dan yang paling penting, kembali dengan kamarku. Ketika aku sampai, rumah terlihat sangat rapi dan bersih. Piring-piring kotor sudah tertata rapi di rak, biasanya sepulang sekolah aku yang selalu mencucinya. Semuanya tampak sangat berbeda. Ketika aku sampai di lantai 2 tepatnya di depan kamar, pintu kamarku terbuka. Aku bergegas masuk. Selama ini tidak ada yang berani untuk masuk ke dalam kamar ini, bahkan Papa sekalipun. Aku tersulut oleh emosi, dadaku naik turun dan nafasku menjadi terasa lebih berat.
“APA YANG BIBI LAKUKAN DI SINI?” kataku tegas, sedikit membentak. Nafasku tersengal-sengal.
“I just cleaning your room, honey. Aku sedang membersihkan rumah ini dan berpikir…”
“EXCEPT MY ROOM!!! Aku tidak menghendaki semua orang, tanpa terkecuali, untuk memasuki kamarku. Tolong lakukan saja apa yang kau mau, tapi tolong jangan ganggu aku. Aku benar-benar tidak tertarik untuk lebih dekat denganmu!” kataku penuh penekanan.
Aku membanting pintu kamar cukup keras, membenamkan wajahku di balik bantal, menangis sejadi-jadinya. Jika dipikir, mungkin ini hanya hal sepele, tapi bagiku ini sudah sangat fatal. Aku bahkan tidak pernah membawa masuk Papa, tapi lihatlah orang asing ini seenaknya masuk ke kamarku. Aku mengambil boneka kelinciku, memeluknya, menangis mendekapnya. Setelah merasa cukup tenang, aku mulai berpikir kalau aku sudah terlalu berlebihan pada Bibi Clara. Aku merenungi diriku yang tak pernah baik.
Lamunanku terbuyarkan oleh seekor burung yang beberapa hari ini sering berkunjung. Ia terbang ke sana kemari lalu terbang keluar. Aku tertarik mengikutinya. Ingin sekali aku melihat rumahnya, melihat keluarga kecilnya. Aku keluar lewat jendela dan berlari beriringan dengan burung itu. Tak sadar sudah jauh aku berlari, tibalah aku di sebuah sungai dengan pemandangan air terjun yang menawan. Aku tertegun, baru kali ini aku melihat pemandangan elok ini. Sementara burung itu terbang ke balik air terjun, aku pun mengikutinya karena tempat ini juga asing bagiku.
Di balik air terjun itu masih ada daun-daun bergelantungan dengan hiasan bunga kecil berwarna biru. Aku menyibak dedaunan bak gorden itu dan terkejut. Mataku membulat sempurna, tanganku menutup mulutku yang menganga. Tak percaya dengan apa yang kulihat, aku beberapa kali mengerjap-ngerjapkan mataku, mencubit lenganku. Nihil. Ini bukan mimpi. Luar biasa!
Sebuah tempat rimbun dengan sabana yang hijau. Langit yang biru bak lautan awan. Kincir yang berputar-putar, bunga dandelion yang seminggu lagi mungkin berterbangan, serta rumah-rumah kayu yang dikreasikan dengan apa yang ada di sana. Memanfaatkan bahan-bahan sekitar. Dan lihatlah orang-orang di sini, mereka sibuk tertawa, bermain, bercocok tanam, dan banyak lagi. Aku melangkah lebih ke dalam sana. Masih tergugu dengan semua ini.
Di bawah pohon rindang, aku melihat seorang wanita sebayaku, memakai dress berwarna biru bercampur kuning menyala. Tunggu, sepertinya aku mengenali wanita ini. Wanita itu menoleh ke arahku, kaget lalu sedikit salah tingkah. Dia membalikkan badan ke arahku lagi, tersenyum manis.
“Hai!” sapanya sambil mengulurkan tangannya. Aku enggan untuk membalas tangannya, tapi selanjutnya aku meraih tangan itu.
“Apakah kau mengikuti burung kecilku?” tanyanya, sedikit menggoda dengan senyum kecilnya itu.
Aku tersenyum kikuk, lalu 3 detik kemudian mengangguk. Dia tertawa.
“Baiklah, karena kau sudah repot-repot mengikutinya, tidak mungkin kalau aku tidak memberimu sebuah pengalaman seru. Tenang, aku akan jadi pemandumu. Panggil saja aku Eli,” katanya sambil mengedipkan sebelah matanya.
“Adel,” jawabku mempersingkat.
“Hmmm, nampaknya kau sedikit pendiam ya, tapi tak mengapa. Aku yakinkan kau akan mendapat sebuah petualangan yang mengasyikkan bersamaku. Ayo, ikuti aku!”
Aku tersenyum simpul. Mengikutinya dari belakang. Sepanjang perjalanan, Eli menjelaskan ini itu sambil menunjuk-nunjuk ke sana ke sini. Aku sangat tertarik. Tak pernah rasanya aku berkeliling seperti ini. Bahkan yang lebih fantastik adalah kota ajaib ini. Bagaikan masuk ke dalam dunia imajinasiku sendiri.
“Lihatlah pak tua itu!” katanya sambil menunjuk lelaki tua yang sedang memanen kebun semangkanya. Eli tertawa entah apa yang ditertawakannya.
“Halo, Pak Hahahahahakim!” teriaknya diselingi tawa.
Eli menyenggol lenganku, tertawa terbahak-bahak. Aku hanya diam, tak mengerti yang dimaksud. Yang dipanggil malah menjulurkan cangkulnya ke arahku dan Eli. Ngeri.
“Jangan mempermalukanku di depan kawan barumu, anak nakal!” katanya kemudian. Dan lihatlah, yang diajak bicara malah makin tertawa puas.
Lelaki tua itu menghampiri kami. Tidak dengan cangkulnya.
“Diam kau!” kata lelaki itu sambil matanya melotot. Eli iseng menahan tawanya.
“Hai, nak! Apakah kau teman si nakal ini? Perkenalkan, namaku Hakim. Cukup kau panggil aku Paman Akim,” katanya centil. Nadanya berubah menjadi sedikit coquettish. Eli tak tahan, ia kembali dengan tawa renyahnya. Sebenarnya aku sedikit geli dengannya, tapi ini lucu sekali.
“Adel,” aku menjawab dengan senyum kecilku.
“Bisakah kau memberi senyuman manismu itu lagi, sayang?” kata Paman Akim menggoda.
Eli yang mendengarnya sedikit jijik dan berlagak mau muntah. Aku tertawa kecil.
“Ahhh, tidakkkkkk!!!! Itu terlalu berlebihan. Manis sekali.”
Kami bertiga sontak tertawa bersama. Sekali lagi, aku tidak pernah tertawa sepuas ini. Benar-benar menyenangkan.
Setelah sempat singgah untuk makan hasil panen Paman Akim, aku dan Eli melanjutkan berkeliling. Kali ini ia membawaku ke pusat kota. Banyak orang berlalu-lalang ke sana kemari, sibuk mempersiapkan sesuatu. Tampaknya akan ada acara besar di sini. Beberapa orang menyiapkan tenda-tenda stand, beberapa lagi memasang spanduk dan lampu yang bergelantungan, ada lagi yang membuat hiasan dari bahan-bahan yang ada. Semuanya serba sibuk, bahkan anak-anak juga sibuk berlari-larian sambil menabur bunga di sepanjang jalan.
“Datanglah malam ini bersamaku. Akan ada festival setiap seratus tahun sekali untuk menyambut bulan biru sempurna. Kami menggelar acara ini berdasarkan jejak nenek moyang kami. Ini akan sangat menyenangkan. Percayalah,” kata Eli menjelaskan.
Aku mengangguk bersemangat. Kami lanjut berkeliling, tapi kali ini tidak berjalan. Kita menaiki balon udara. Eli sangat lihai dalam menggunakannya, mulai dari menghidupkan api, mengatur angin, melepas jangkar, dan memandu arah balon itu. Kami terbang tinggi, lalu tahukah kalian, sekarang kita berhenti di mana? Ini mustahil. Di atas awan. Benar. Ini bukan awan yang terbentuk dari penguapan air di laut, berbeda. Ini adalah gumpalan kapas yang empuk. Aku benar-benar tak habis pikir dengan semua kemustahilan ini.
Eli mengajakku turun. Awalnya aku ragu untuk menginjak gumpalan awan itu sebelum Eli menarik lenganku. Aku sedikit terperanjat, lalu sedetik kemudian aku tertegun. Luar biasa. Aku meloncat-loncat ke sana kemari, begitu pun Eli. Lalu kami berhenti di bawah pohon. Pohon yang daunnya adalah awan dan buahnya adalah kristal-kristal air. Kalian salah jika mengira warna awan adalah sempurna putih. Di sini, kalian akan menemukan awan dengan berbagai warna. Bahkan kolam awan pun ada. Lucu sekali memang. Aku menikmati semua ini, aku menghamburkan badanku ke awan-awan lembut ini. Dari sini, aku bisa melihat pelangi yang indah, dan lihatlah, sebentar lagi mentari akan bersembunyi. Langit perlahan berubah menjadi pink keunguan, bergradasi dengan semburat oranye dan merah. Indah sekali.
“Tahukah kau, sebenarnya kami ini apa?” Eli membuka percakapan.
Aku tersenyum menggeleng sambil menatap wajah cantik Eli yang juga membaringkan tubuhnya di sampingku. Eli menikmati suasana sore ini. Matanya terfokuskan ke atas, sambil sesekali menghirup udara segar.
“Kau akan segera mengetahuinya.”
Eli tersenyum, lalu sejurus kemudian menarik tanganku, membuat tubuh kami meloncat dari dalam balon udara. Aku terkejut bukan kepalang, panik, marah, takut, entah, semuanya bercampur aduk.
“ELI, APA KAU SUDAH GILA!!! KITA AKAN TERJUN DAN SEGERA MATI! SUNGGUH, KAU SUNGGUH GILA!” aku berteriak memakinya, merutuki tindakan bodohnya.
Lalu Eli melepaskan genggamannya. Ini gila.
“Tenanglah, Adel. Rentangkan tanganmu seperti ini dan nikmati penerbangan kita.”
“Kau sungguh gila! Bagaimana mungkin aku bisa setenang itu?”
“Hahaha. Tak perlu risau, semuanya akan menyenangkan. Aku berjanji,” ucap Eli sambil tersenyum menampakkan gigi rapinya.
Aku menarik napas, menahannya beberapa detik dengan mata terpejam, berusaha mencari ketenangan, kemudian membuangnya. Oke! Sekarang aku mulai mengikuti kata si gila Eli, membentangkan kedua tanganku lalu mengatur napasku. Kemudian perlahan membuka mataku.
“Adel!! Kau berhasil!!!” teriak Eli senang.
Aku tak percaya, aku terbang. Wiiiiii, asyik sekali. Layaknya burung yang lihai dengan sayapnya, aku berhasil menaklukannya. Aku terbang menikmati indahnya pemandangan dunia ini, senang bukan main. Di bawah adalah sabana dengan bunga-bunga dandelion yang siap untuk menyambutku. Aku terbang meluncur di atasnya, membuat bunga-bunga itu rontok dan berhamburan. Aku sempat mengambil satu tangkai edelweiss yang siap untuk ku tiup. Satu, dua, dan hufttttt, bunga itu sudah berceceran terbang. Konon katanya, dandelion adalah bunga harapan yang bisa mengabulkan harapan-harapan kita. Maka dari itu, sebelum aku meniup bunga tadi, aku sudah merapalkan harapanku. Rahasia.
Hari mulai gelap, aku terbang mengikuti Eli dari belakang. Kemudian kita mendarat di sebuah rumah indah. Rumah itu kecil dan sederhana tapi sangat indah. Di pelatarannya ada lampu yang mirip dengan bunga terompet yang terbalik. Bangunan rumahnya terbuat dari batang pohon besar yang kemudian dipotong memanjang, lalu ditambahkan 2 pintu setengah lingkaran yang dikaitkan sehingga membentuk lingkaran sempurna. Jendelanya kotak dan ada beberapa pot bunga di sana. Tak hanya itu, rumah itu dipenuhi tumbuhan rambat yang berbunga biru, ungu, dan putih kecil-kecil.
Ketika Eli membuka pintu, terdapat suara bel. Aku berjalan perlahan memasuki rumah itu, melihat sekeliling, sangat luar biasa. Bangunan arsitektur yang sederhana tapi menarik. Di dalamnya sangat minimalis, hanya ada tempat tidur dengan meja rias yang di bawahnya dipadukan dengan rak buku dan segala aksesoris. Selain itu, di atas meja rias itu terdapat sebuah lampu tidur berbentuk jamur yang bisa mengeluarkan tetes-tetes air seperti air hujan, di bawah lampu itu ada penampungan airnya sekaligus, dan air itu mengeluarkan uap serta suara gemericik hujan. Sangat tenang. Di sebelah meja rias itu ada sebuah lemari besar tempat baju dan ada rak sepatu yang tergelantung. Lalu di bagian langit-langit adalah gambar lampion-lampion yang berterbangan dengan bintang-bintang kecil. Di sebelah kanan ruangan ada sebuah meja dan 2 buah kursi yang saling berhadapan, lalu ada rak yang sepertinya merupakan rak makanan. Dan ini yang lebih menarik, di sisi samping meja makan adalah tempat untuk melukis, ada berbagai peralatan yang tersedia di sana.
Aku melirik ke arah Eli, yang ditatap tersenyum mengangguk seakan mengerti maksudku. Aku menghampiri ruang melukis itu, meraba berbagai lukisan di sana dan melihat sekeliling. Benar-benar luar biasa. Semua ini membuatku terpana.
“Adel, bersiaplah. Sebentar lagi festival akan dimulai,” ucap Eli mengingatkan.
Aku mengangguk kemudian mandi. Eli sudah menyiapkan baju untukku. Baju itu adalah sebuah dress tanggung tidak berlengan berwarna pastel, kemudian akan dicombo dengan sebuah rompi berenda warna putih. Sangat pas di tubuhku. Rambut depan sisi kanan dan kiri ku kepang, kemudian kutambah pita berwarna pastel juga. Aku memakai flatshoes berwarna hitam berkilau. Sedangkan Eli, ia mengenakan sebuah rok di atas tumit warna putih bermotif bunga putih juga, kemudian bagian atasnya mengenakan croptop berwarna hijau polos. Eli membiarkan rambutnya tergerai, kemudian ia mengenakan penjepit berbentuk bunga daisy di sisi kanan dan kiri rambutnya. Tampak cantik sekali. Lalu untuk sepatunya, ia menggunakan sepatu boots ber-high heels warna coklat. Dan sebagai sentuhan terakhir, kita harus menggunakan topeng mata saat nanti festival.
Setibanya di pusat kota, pemandangan dipenuhi oleh ramai orang bertopeng yang lucu-lucu. Banyak anak-anak berlari-larian, dan setiap tenda stand ramai pengunjung. Eli menggenggam tanganku supaya kita tidak terpisah oleh ramainya massa. Lampu-lampu berkelap-kelip, suara alat musik juga terdengar remang-remang. Aku dan Eli berhenti di sebuah pertunjukan teater yang berjudul SnowWhite X Hiphop. Alur ceritanya masih menggunakan latar kisah Snow White, namun pakaian dan properti yang mereka gunakan lebih modern dan mengikuti tren zaman sekarang. Beberapa kali para penonton dibuat tertawa oleh tingkah para aktor teater itu. Aku dan Eli pun sama, kami tertawa terbahak-bahak ketika nenek penyihir itu salah mengambil benda dalam tasnya. Yang seharusnya mengambil apel, malah tertukar dengan seekor kelinci, lalu ketika berusaha mengambil lagi, malah tertukar dengan telur ayam yang ternyata induknya sudah marah-marah di bawah kakinya. Menyenangkan sekali.
Kini tibalah saat yang kita nantikan. Menyambut bulan biru sempurna. Orang-orang berbondong-bondong ke atas bukit, begitu pun aku dan Eli. Eli mengajakku ke sebuah tempat yang tak banyak orang tahu, untuk menyaksikan bulan itu. Tepatnya di sabana dandelion tadi. Aku sangat senang menikmatinya bersama Eli.
Bulan sudah mulai terlihat. Langit malam ini cerah sehingga bulan akan terlihat lebih jelas. Aku dan Eli duduk bersisian menanti bulan itu. Saat bulan itu sudah muncul lebih dari setengah, kita berhitung mundur secara bergantian. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan yah! Bulan biru sempurna. Sangat indah sekali. Aku sampai tak bisa berkata-kata. Aku hanya diam menggenggam tangan Eli, begitu pun Eli, ia juga menikmati pemandangan langka ini.
Tak lama setelah itu, tampak bintang-bintang yang jatuh. Indah sekali. Namun setelah beberapa saat, bintang itu semakin tidak beraturan. Tampaknya kita salah, itu adalah hujan meteor yang menyerang. Kami beranjak berdiri lalu bergegas pergi dari sabana. Namun, terlambat. Sebuah meteor jatuh di ladang sabana ini. Kita terpental jauh. Tak sadarkan diri. Entah masih selamat atau tidak.
Aku mengerjap-ngerjapkan mataku. Telingaku berdengung nyaring, kepalaku pusing sekali, badanku terasa ngilu. Seketika aku tersadar. Eli! Di mana Eli? Bagaimana ini, apa yang harus aku lakukan? Perlahan aku bangkit berdiri walau masih sangat lemas. Aku terjebak di sini sendirian, tak ada seorang pun yang bisa kutanya. Aku melihat sekelilingku, hanya sabana yang kosong di tengah gelapnya malam dan hanya cahaya bulan biru sempurna yang menerangi. Aku berjalan mencari ujung dari sabana ini. Tapi semakin jauh aku berjalan, aku semakin terjebak. Tempat apa ini? Di mana aku? Di mana semua orang?
Aku mulai frustasi dan merasa tak sabar. Aku berlari menyusuri sabana ini. Sial!!! Tempat ini tak berujung. Aku kelelahan, seketika aku teringat Eli dan aku pernah terbang menyusuri ladang sabana ini. Aku mencoba membentangkan tanganku, menutup kedua mataku, menarik napas lalu membuangnya. Percuma. Tak ada apa pun yang terjadi. Aku menangis tersedu, menyadari semua hal yang tak berguna ini.
Bawa aku kembali. Ucapku merutuki nasibku saat ini. Lalu tiba-tiba datanglah angin yang begitu kencang. Aku tak bisa menahan tubuhku. Aku terbawa oleh arus angin, terpontang-panting tak tentu arah. Lalu kemudian, BYURRRR!!!! Aku jatuh ke dalam lautan, dingin, sesak. Badanku sudah tak berdaya lagi. Aku semakin tenggelam dalam laut itu. Pasrah dengan apa yang terjadi, aku berpikir kalau hidupku sudah sampai di sini. Selamat tinggal semua, Papa, Bibi Clara. Mungkin sebentar lagi aku akan bertemu Mama. Mataku mulai terpejam, semuanya menggelap.
Lagi-lagi aku terbangun, tapi kali ini di sebuah ruang. Aku duduk di sebuah kursi. Tak ada apa pun di sini. Ruang kosong. Hanya ada satu cahaya di sini, yaitu cahaya yang menyorotiku. Aku menangis, tak tahu apa yang terjadi. Perasaan bingung, kesal, lelah, sedih, marah, semua bercampur menjadi satu. Lalu datanglah seekor burung kecil. Burung yang selalu aku lihat.
“Bisakah kau membawaku kembali?” kataku sambil terisak.
Burung itu terbang, aku berjalan mengikutinya dari belakang. Anehnya, ruang gelap itu menjadi bercahaya ketika aku berjalan melewatinya. Lalu sampailah di ujung, terdapat sebuah pintu. Aku membukanya, dan itu adalah pintu di atas awan. Benar. Aku meloncat, mengingat aku pernah melakukan ini sebelumnya bersama Eli. Aku mulai memejamkan mataku, menarik napas sedalam-dalamnya lalu membentangkan tanganku, kemudian menghembuskan napasku dan membuka mata. Nihil. Ini tak bekerja. Aku mencobanya lagi. Nihil. Sekali lagi. Nihil.
Aku mulai panik, apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa aku bisa sampai di sini? Akhirnya BYURRR!!!! Aku tercebur ke dalam lautan lagi. Lagi-lagi aku tak bisa berbuat apa pun. Badanku semakin tenggelam ke dalam lautan, tapi kemudian ada seseorang menarik tanganku ke atas. Badanku perlahan naik. Itu adalah Eli. Aku terkejut, tapi tak bisa berbuat apa pun. Tapi kemudian, tubuh Eli berubah menjadi semakin tua, tidak lagi seperti sebaya, lebih mirip orang dewasa. Lalu aku tersadar, dia bukanlah sosok asing bagiku. Itu Mama. Ya, tidak salah lagi. Mama. Aku ingin menangis, menjerit, memanggilnya, tapi aku tak bisa. Aku mengeratkan genggaman tangannya. Lalu ketika hampir sampai di permukaan, Mama mendorongku naik ke atas, disusul sebuah tangan yang menarikku dari permukaan. Mama menatapku, tersenyum lewat matanya, aku menggenggam tangannya lebih kuat, tapi selesai semua itu percuma. Genggaman kita terlepas sempurna, dan semuanya menjadi gelap.
Aku terbangun, napasku tersengal-sengal. Badanku basah. Apa yang terjadi? Di mana Mama? Aku terisak memanggil-manggil Mama. Seseorang mendekapku. Bibi Clara, ia juga ikut terisak bersamaku, mengelus pundakku, menciumi puncak kepalaku.
“Syukurlah kau selamat. Aku sangat mengkhawatirkanmu, maafkan aku,” ucap Bibi Clara diselangi isaknya.
Aku menggeleng, mengeratkan dekapanku. Bibi Clara balas mendekapku erat, mencium kepalaku.
“Ayo, kita pulang,” ajaknya mengakhiri.
Aku mengangguk mengiyakan. Sesampainya di rumah, Bibi Clara membantuku sampai di kamarku. Ia memintaku untuk membersihkan diri terlebih dahulu kemudian istirahat. Di bawah, Bibi Clara mengotak-atik peralatan dapur. Aku melirik jam, pukul 15.00. Ternyata baru jam 3 sore, jadi aku hanya pergi selama 2 jam saja. Sungguh mustahil. Tapi itulah kenyataannya.
Bibi Clara kembali, ia mengetok pintu kamarku. Kemudian membuka pintu dan membawakanku susu hangat dan juga bubur. Lalu ia menyuapiku. Aku hampir meneteskan air mata dengan sikap perhatiannya.
“Aku sangat menyesal sudah bertindak seenaknya. Tolong maafkan aku,” ucap Bibi Clara memohon.
Aku menggapai tangannya, tersenyum, dan menggeleng.
“Kita bisa memperbaikinya,” jawabku meyakinkan.
Bibi Clara tersenyum lalu mendekapku. Setelah beberapa saat, Papa kembali dari kegiatan golf-nya. Ia khawatir denganku, tapi Bibi Clara meyakinkannya bahwa aku baik-baik saja. Aku ingin istirahat, tapi aku teringat semua kejadian mustahil itu. Aku menatap langit-langit kamarku yang berbeda dengan langit-langit kamar Eli. Lalu aku beralih menatap menyusuri setiap detail ruang ini, hingga aku berhenti di tempat biasanya aku melukis. Aku berpikir dalam, merasakan kejanggalan.
Lukisan!! Ya, benar!
Semua kejadian mustahil yang aku alami adalah semua lukisanku. Aku masuk ke dalam dunia lukisanku sendiri. Mulai dari kota ajaib itu, lalu ladang sabana dandelion itu, lalu sunset di atas awan, lalu hujan meteor, lalu ruang gelap dan kosong dengan satu sorot cahaya yang menyinari, hingga lukisan seseorang yang menarik tanganku di dalam laut itu. Semuanya adalah perwujudan dari lukisanku. Tak kusangka, aku benar-benar masuk ke dalamnya. Aku kembali terisak, rinduku kepada Mama semakin menguak. Lalu aku tertidur dengan mendekap figura foto keluargaku. Esok aku akan bangun, dan menjalani dunia yang sesungguhnya.
Aku terjebak dalam lingkaran hitam yang aku buat sendiri. Lewat semua petualangan ini, aku hanya perlu berdamai dengan diriku sendiri. Memaafkan diriku di masa lalu, dan memeluk rasa sakitku. Tidak ada yang perlu disesali, dibenci. Life isn’t a competition. Hidup itu bukan sebuah kompetisi tentang menaklukkan orang lain, tapi tentang menaklukkan diri sendiri dan berdamai dengan semuanya. Matahari akan selalu menepati janji, bahkan di hari yang paling buruk seumur hidupmu.
-Tamat-
THE POWER OF LIFE – Dian Elisaningtiyas